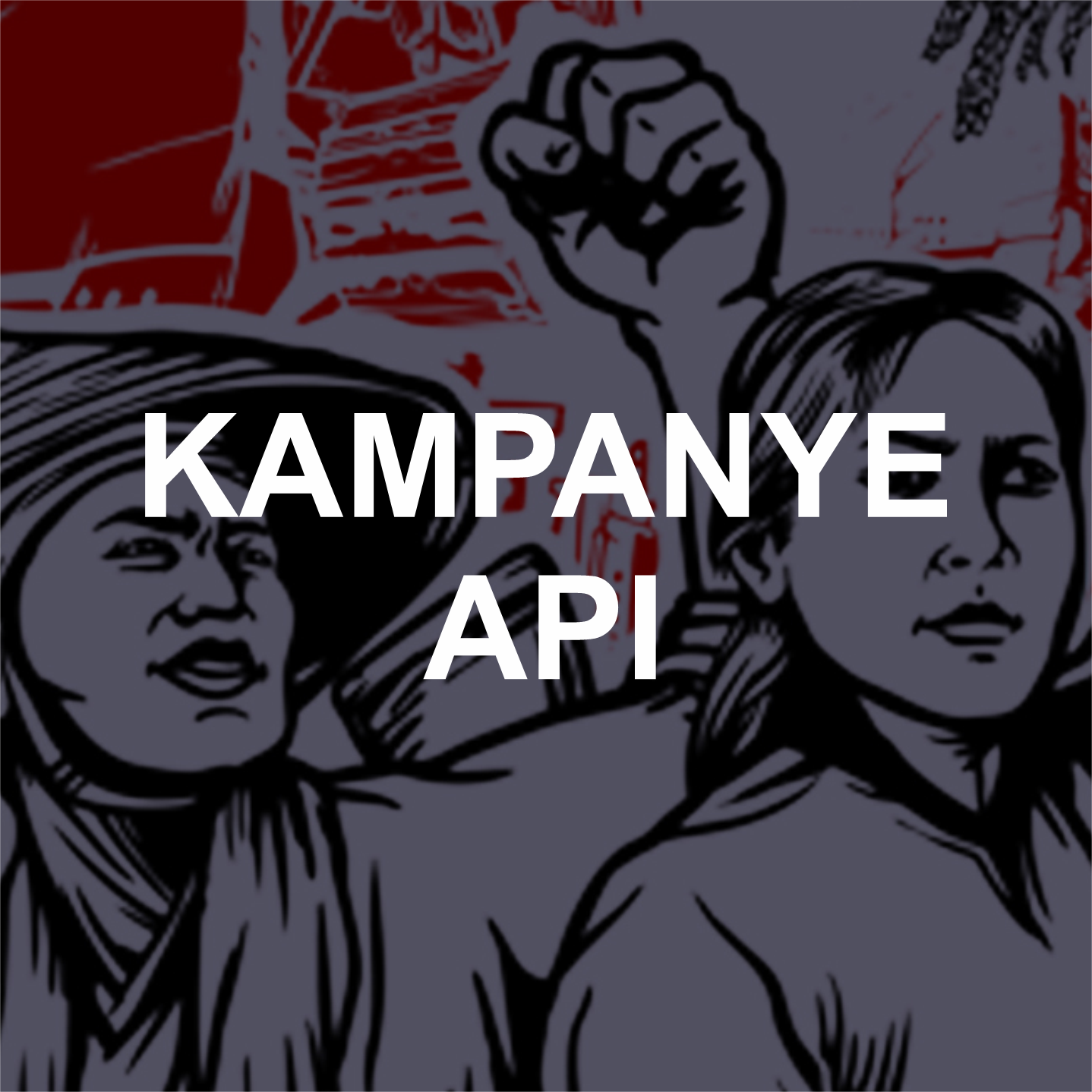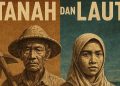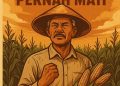Sejarah kebijakan agraria di Indonesia pasca-kemerdekaan ditandai oleh pergeseran ideologis yang signifikan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menjadi “tonggak” penting yang menegaskan bahwa reforma agraria adalah penataan ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan bagi kemakmuran rakyat. Namun, semangat awal ini mengalami kemunduran drastis di era Orde Baru.
Pada era ini, kebijakan agraria dan pangan sangat terpusat dan berorientasi pada swasembada beras. Tujuannya adalah untuk mencapai kemandirian pangan melalui peningkatan produksi secara besar-besaran. Kebijakan utamanya meliputi:
- Revolusi Hijau: Pemerintah menerapkan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Program-program seperti Bimbingan Massal (Bimas) dan Intensifikasi Massal (Inmas) digalakkan untuk mendorong penggunaan benih unggul, pupuk, pestisida, dan teknologi modern. Hal ini berhasil meningkatkan produksi beras dan mencapai swasembada pada tahun 1984.
- Sentralisasi Kebijakan: Peran pemerintah, khususnya melalui Bulog (Badan Urusan Logistik), sangat dominan. Bulog memiliki monopoli dalam pembelian gabah petani dan mengendalikan harga untuk menjaga stabilitas pasar.
- Kecenderungan Pengabaian Reforma Agraria: Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 ada, implementasi reforma agraria (penataan ulang kepemilikan tanah) tidak berjalan efektif. Sebaliknya, lahan dikonsentrasikan untuk proyek-proyek besar, yang sering kali memicu konflik agraria dan meminggirkan petani kecil.
Kebijakan agraria pada masa ini tidak lagi berfokus pada redistribusi tanah untuk petani kecil, melainkan bergeser menjadi “tanah untuk pembangunan”. Land reform direduksi menjadi isu administratif-teknis, dan partisipasi organisasi petani dihapuskan. Pergeseran ini menciptakan jurang ketimpangan yang mendalam dalam kepemilikan dan penguasaan tanah, sebuah warisan struktural yang masih memengaruhi lanskap agraria hingga kini.
Era Reformasi – Presiden KH. Abdurahman Wahid
Pemerintahan Gus Dur menghadapi tantangan transisi pasca-Orde Baru. Kebijakan pangan diarahkan pada sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keanekaragaman sumber daya dan kearifan lokal. Meskipun begitu, kebijakan ini masih berbenturan dengan kenyataan ekonomi, seperti tingginya harga sarana produksi dan impor beras yang membanjiri pasar, menyebabkan harga gabah petani anjlok. Pemerintah mulai mencoba mengurangi peran Bulog dan mendorong efisiensi di sektor pertanian.
Gus Dur seringkali mengkritik kebijakan agraria Orde Baru yang merugikan rakyat. Ia secara blak-blakan menyatakan bahwa banyak lahan perkebunan dan kehutanan, termasuk lahan Perhutani, yang dahulu merupakan tanah milik rakyat yang direbut atau diserobot secara paksa oleh pemerintah dan korporasi. Pernyataan ini memberikan legitimasi moral dan politik bagi perjuangan rakyat untuk merebut kembali tanah mereka yang hilang.
- Pemicu Konflik Lahan: Pernyataan Gus Dur ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan pendudukan lahan bukanlah “kejahatan”, melainkan upaya untuk mendapatkan kembali hak mereka yang terampas. Hal ini memicu gelombang pendudukan lahan oleh petani di berbagai wilayah, terutama di kawasan hutan Perhutani dan perkebunan besar.
- Pengakuan dan Rekonsiliasi: Gus Dur memandang bahwa pendudukan lahan ini adalah konsekuensi dari ketidakadilan masa lalu. Sikapnya yang simpatik terhadap perjuangan rakyat ini berbeda jauh dengan pendekatan represif yang biasa dilakukan di masa sebelumnya. Ia mendorong pendekatan damai dan penyelesaian konflik melalui dialog, bukan kekerasan.
- Landasan Kebijakan: Meskipun tidak sempat mengesahkan TAP MPR IX/2001, pemerintahan Gus Dur memberikan ruang bagi wacana reforma agraria untuk berkembang. Sikap dan pernyataannya membuka jalan bagi pengakuan negara atas ketimpangan agraria yang telah lama terjadi. Hal ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya TAP MPR tersebut di era berikutnya, yang secara resmi mengamanatkan pelaksanaan reforma agraria.
Masa Presiden Megawati
Pada era ini, wacana kedaulatan pangan mulai didorong sebagai alternatif dari sekadar ketahanan pangan. Kedaulatan pangan berarti kemampuan negara dan rakyat untuk menentukan kebijakan pangan sendiri, tanpa bergantung pada impor. Megawati menekankan pentingnya pengembangan sumber daya lokal dan mendorong riset untuk menemukan benih unggul yang sesuai dengan keragaman hayati Indonesia. Meskipun niatnya baik, masalah struktural seperti impor yang terus berlanjut dan konflik agraria yang meluas tetap menjadi isu krusial yang belum terselesaikan.
TAP MPR tentang reforma agraria, yaitu TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, disahkan pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
TAP MPR ini menjadi landasan hukum yang penting bagi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Tujuannya adalah untuk menata ulang kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta menyelesaikan berbagai konflik agraria yang terjadi.
Masa Presiden SBY
Pemerintahan SBY meluncurkan program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dengan tujuan memberdayakan petani dan menjadikan pertanian sebagai penggerak ekonomi. Kebijakan ini berfokus pada:
- Peningkatan kesejahteraan petani: SBY berjanji untuk tidak hanya memajukan sektor pertanian, tetapi juga meningkatkan taraf hidup petaninya.
- Modernisasi Pertanian: Mendorong penggunaan teknologi, permodalan, dan perbaikan infrastruktur seperti irigasi dan jalan usaha tani.
- Liberalisasi terbatas: Kebijakan SBY cenderung lebih liberal dibandingkan pendahulunya, tetapi masih menjalankan kebijakan proteksionis untuk komoditas tertentu. Salah satu program yang menonjol adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang ditujukan untuk memberikan akses modal bagi petani dan UMKM.
Namun, pada masa SBY pula program food estate mulai digagas sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, meskipun implementasinya kemudian menuai kritik karena ketidaksesuaian lahan dan pendekatan yang sentralistik. Secara ringkas, perpindahan kekuasaan dari Orde Baru ke era Reformasi menunjukkan pergeseran dari paradigma produksi massal yang sentralistik menuju paradigma yang lebih memperhatikan aspek kesejahteraan petani, kedaulatan, dan keanekaragaman pangan, meskipun implementasi dan hasilnya masih menjadi perdebatan
Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan Era Jokowi
Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan reforma agraria dan kedaulatan pangan sebagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024. Kebijakan ini berlandaskan pada dua pilar utama, yaitu Penataan Aset (redistribusi tanah dan legalisasi aset) dan Penataan Akses (pemberian akses permodalan dan bantuan lain). Analisis data menunjukkan bahwa fokus utama dari program ini adalah legalisasi aset, yaitu pensertifikatan tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegangnya. Hingga November 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat legalisasi aset lahan telah mencapai 10.7 juta hektar, jauh melampaui target awal sebesar 4.5 juta hektar.
Namun, realisasi yang paling krusial bagi petani kecil, yaitu redistribusi tanah, jauh tertinggal. Dari target 4.5 juta hektar redistribusi, hanya 392.370 hektar yang terealisasi di kawasan hutan, atau hanya 9.57 persen dari total target. Organisasi masyarakat sipil menilai bahwa komitmen politik pemerintah dalam menjalankan reforma agraria dan kedaulatan pangan sangat lemah. Kritik ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 yang dianggap bertentangan dengan tujuan reforma agraria, serta kebijakan Bank Tanah yang dituding memfasilitasi liberalisasi agraria dan mengabaikan penyelesaian konflik.
Proyek Food Estate merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diluncurkan oleh pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2020 sebagai respons terhadap kekhawatiran krisis pangan global akibat pandemi Covid-19. Proyek ini dirancang untuk menciptakan kawasan produksi pangan skala besar dan terintegrasi di lahan yang sangat luas. Namun, program ini menuai kritik tajam karena dinilai gagal mencapai target dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan, terutama dari perspektif ekologi dan sosial. Proyek-proyek ini sering kali mengalami kendala, mulai dari perencanaan yang tidak matang hingga isu kepemilikan lahan yang menimbulkan konflik. Aliansi Petani Indonesia juga menyoroti adanya impor pangan masif, terutama beras yang diperkirakan mencapai 5 juta ton hingga akhir 2024, yang kontradiktif dengan narasi swasembada. Fenomena ketidakstabilan harga, di mana Harga Pembelian Gabah (HPP) tidak sebanding dengan biaya produksi, juga terus merugikan petani.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan agraria dan pangan di Indonesia pasca-Orde Baru bukanlah perubahan radikal, melainkan sebuah kelanjutan dari model pembangunan yang sentralistik dan korporasi. Kegagalan program reforma agraria dan proyek food estate, importasi pangan terutama beras bukanlah anomali, tetapi merupakan fitur dari sistem yang secara konsisten memprioritaskan kepentingan modal besar dan negara. Narasi kebijakan yang pro-rakyat berfungsi sebagai legitimasi ideologis, sementara di balik layar, struktur ketidak setaraan dalam penguasaan tanah tetap dipertahankan. Pola ini menunjukkan bahwa, terlepas dari janji-janji politik, kebijakan yang ada tetap tunduk pada logika hegemoni yang mengedepankan kontrol elite atas sumber daya agraria.
Kebijakan Reforma Agraria Prabowo Subianto
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengartikulasikan visi dan misi yang jelas terkait reforma agraria dan kedaulatan pangan. Program prioritasnya mencakup pencapaian swasembada pangan, pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi. Menekankan bahwa tidak ada bangsa yang merdeka tanpa menguasai pangan sendiri, mencatatkan cadangan beras terbesar dalam sejarah (4,2–4,4 juta ton), meningkatkan produksi beras dan jagung hingga 48–50% dalam waktu singkat dan menindak praktik manipulasi harga dan distribusi pangan. Program food estate dilanjutkan, khususnya untuk komoditas seperti padi, jagung, kedelai, tebu, dan tanaman lokal seperti sagu, singkong.
Untuk mendukung visi ini, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengumumkan ketersediaan 864.662 hektare tanah potensial dari cadangan tanah telantar dan konversi Hak Guna Usaha (HGU). Dari jumlah tersebut, 209.780 hektare dialokasikan untuk program ketahanan pangan, 567.585 hektare untuk transmigrasi, dan 77.297 hektare untuk perumahan rakyat. Dari sudut pandang ortodoks, data-data ini mengindikasikan adanya rencana yang terukur dan terarah untuk mengelola sumber daya agraria demi kepentingan nasional. Visi yang disajikan melalui narasi Asta Cita tampak rasional dan berorientasi pada hasil, sebuah pendekatan yang diharapkan akan menyelesaikan permasalahan tanah dan pangan.
Pangan-Pertahanan: Narasi Patriotik untuk Konsensus Politik
Salah satu elemen kunci dari kebijakan kedaulatan pangan Prabowo adalah kerangka ideologis yang menghubungkan pangan dengan isu pertahanan nasional. Pangan tidak lagi hanya dianggap sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai bagian integral dari strategi pertahanan. Dokumen resmi Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa ketahanan pangan yang kuat mengurangi ketergantungan pada impor, melindungi negara dari ancaman eksternal seperti embargo, dan menstabilkan sosial politik. Narasi ini adalah langkah strategis untuk membangun konsensus publik yang kuat. Dengan menaikkan status pangan menjadi isu patriotik, pemerintah dapat membenarkan alokasi dana besar dan keterlibatan aktor-aktor non-sipil dalam proyek-proyek pangan, sebuah tindakan yang mungkin kontroversial dalam konteks lain. Diskursus ini membuat kebijakan-kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat kecil menjadi lebih mudah diterima.
Konsep Food Estate sebagai Wujud Kapitalisme Agraria
Program Food Estate secara konseptual adalah perwujudan dari kapitalisme agraria. Proyek ini mengubah tanah dari sumber mata pencaharian subsisten menjadi alat produksi yang dikelola untuk akumulasi keuntungan. Alih-alih memberdayakan petani sebagai subyek yang berdaulat, mereka disubordinasikan ke dalam rantai pasok industri, menjadi buruh, mitra, atau pemasok di bawah kendali korporasi atau negara. Klaim keberhasilan panen dan harga gabah yang stabil mungkin terjadi, tetapi dalam skema ini, keuntungan terbesar seringkali dinikmati oleh pihak yang menguasai alat produksi dan rantai pasok hulu-hilir, bukan petani kecil itu sendiri.
Simbiosis Kekuasaan: Militer, Korporasi, dan Negara
Kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan di bawah pemerintahan Prabowo merupakan perwujudan dari sebuah simbiosis kekuasaan antara militer, korporasi, dan negara. Keterlibatan militer dalam proyek food estate bukanlah sekadar tugas tambahan, melainkan sebuah peran fungsional yang memungkinkan rezim untuk menegakkan agenda ekonominya. Hal ini menciptakan sebuah saluran yang kuat dan kurang akuntabel bagi kepentingan modal untuk mengakses dan menguasai sumber daya alam secara masif. Tulisan dari The Indonesian Institute (TII) mencatat bahwa proyek strategis nasional, seperti perumahan dan food estate, sangat melibatkan korporasi-korporasi besar dengan partisipasi masyarakat sipil yang sangat minim.
Narasi “Pangan-Pertahanan” memberikan pembenaran ideologis, sementara kolaborasi antara militer dan korporasi menciptakan mekanisme praktis untuk mengamankan lahan dan sumber daya. Proses ini secara efektif membungkam suara-suara kritis dan memastikan bahwa model pembangunan yang sentralistik dan korporasi terus berjalan, meskipun bukti empiris menunjukkan kegagalannya. Ini adalah cerminan dari bagaimana kekuasaan dikonsolidasikan melalui patronase fiskal dan aliansi elite yang kuat.
Sistem ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis atau kebutuhan masyarakat akar rumput, tetapi untuk melayani kepentingan jaringan elite yang terjalin erat. Pendekatan ini secara inheren mengabaikan aspirasi masyarakat adat dan petani kecil, karena tujuan utamanya adalah mempercepat konsolidasi kekuasaan dan kekayaan di tangan segelintir aktor. Konflik-konflik agraria yang terjadi akibat program-program ini tidak dilihat sebagai kegagalan kebijakan, melainkan sebagai efek samping yang dapat ditoleransi dalam upaya mencapai tujuan strategis yang lebih besar, yang disamarkan dalam narasi patriotik.
Dampak Kebijakan terhadap Petani Kecil
Dampak dari kebijakan agraria dan pangan saat ini sangat beragam bagi petani kecil. Di satu sisi, ada klaim keberhasilan yang menyoroti kenaikan harga gabah, kestabilan harga jagung, dan bantuan alat pertanian yang mempermudah pengolahan lahan. Namun, di sisi lain, kritik yang lebih luas menunjukkan bahwa petani kecil menghadapi tantangan eksistensial. Mereka berisiko kehilangan lahan dan mata pencaharian tradisional mereka karena perluasan Food Estate. Model pertanian skala besar ini tidak hanya mengubah hubungan produksi, tetapi juga mengikis identitas budaya dan kearifan lokal, seperti praktik pertanian swidden (berladang) yang tidak cocok dengan pertanian intensif.
Tantangan Ekologis dan Sosial
Percepatan proyek Food Estate juga membawa tantangan ekologis dan sosial yang serius. Pembukaan lahan di area gambut, seperti yang terjadi di Kalimantan, berisiko tinggi merusak ekosistem dan memicu bencana lingkungan. Secara sosial, kebijakan ini berpotensi meningkatkan konflik agraria yang dipicu oleh perebutan lahan. Penolakan dari masyarakat adat di Papua terhadap proyek Food Estate seluas 2 juta hektar di Merauke adalah salah satu indikasi kuat dari perlawanan terhadap proyek yang mengancam keberlangsungan hidup mereka.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Tulisan ini menyimpulkan bahwa analisis kebijakan ortodoks tidak memadai untuk memahami dinamika di balik kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan mengadopsi kerangka hegemoni, terungkap bahwa narasi resmi yang berfokus pada target, efisiensi, dan pertahanan nasional hanyalah lapisan permukaan. Di bawahnya, kebijakan-kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengkonsolidasikan kekuasaan melalui patronase fiskal dan simbiosis antara militer, korporasi, dan negara.
Divergensi antara janji politik dan realitas di lapangan, peningkatan konflik agraria, dan marginalisasi masyarakat adat adalah konsekuensi logis dari model hegemoni ini. Kegagalan-kegagalan masa lalu tidak dianggap sebagai pelajaran, tetapi sebagai alasan untuk melanggengkan proyek-proyek yang menguntungkan segelintir elite. Tanpa perubahan mendasar, kebijakan-kebijakan ini akan terus mereproduksi ketidaksetaraan, bukan menyelesaikannya.
Berdasarkan analisis ini, diajukan beberapa rekomendasi kebijakan alternatif yang menantang model hegemoni:
- Demiliterisasi Kebijakan Pangan: Mengembalikan tata kelola pangan sepenuhnya ke institusi sipil dan demokratis, membatasi peran militer pada fungsi pertahanan yang sah, bukan pada proyek-proyek pembangunan.
- Reorientasi Reforma Agraria: Mendesak pemerintah untuk kembali pada semangat UUPA 1960 dengan memprioritaskan redistribusi tanah kepada petani kecil dan masyarakat adat, serta mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat.
- Transparansi dan Partisipasi Sejati: Mewajibkan proses kebijakan yang transparan dan partisipatif, di mana masyarakat sipil, petani, dan masyarakat adat terlibat secara bermakna dalam perumusan, implementasi, dan pengawasan kebijakan agraria dan pangan.
- Reframing Kedaulatan Pangan: Mengalihkan narasi kedaulatan pangan dari isu pertahanan nasional menjadi isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Hal ini berarti memprioritaskan hak atas pangan, akses terhadap sumber daya produktif, dan perlindungan ekologis, alih-alih proyek-proyek skala besar yang korporasi-sentris.