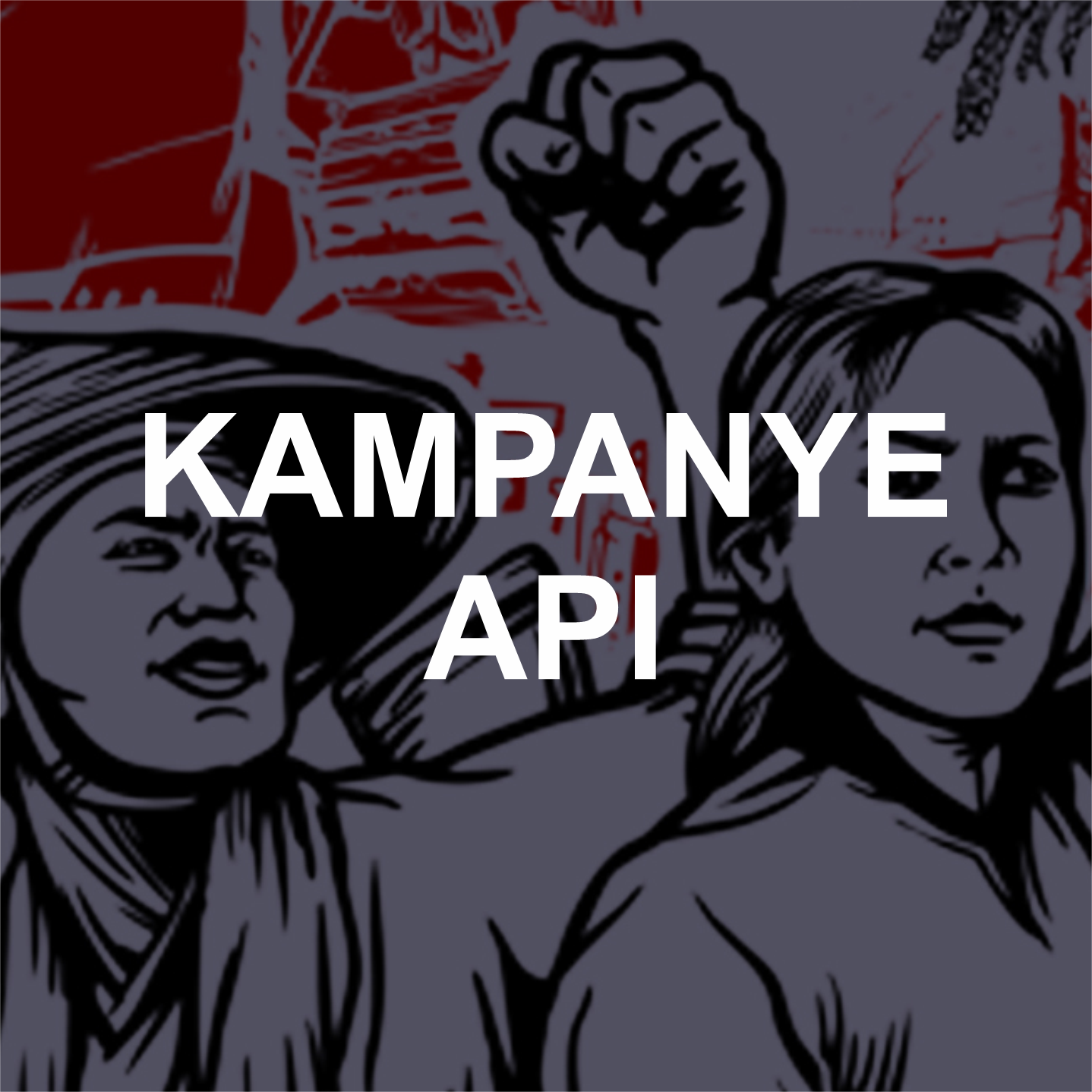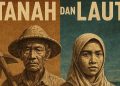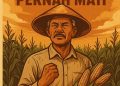Muhammad Nuruddin
Pendahuluan: Lumbung yang sunyi, Gudang yang bising
Di banyak desa Indonesia, lumbung bukan sekadar tempat menyimpan gabah. Ia adalah simbol kedaulatan, solidaritas, dan ritme hidup agraris yang diwariskan lintas generasi. Namun, dalam dekade terakhir, lumbung-lumbung itu perlahan sunyi. Sebaliknya, gudang-gudang korporasi di pinggir kota dan kawasan industri semakin bising: dipenuhi logistik, barcode, dan algoritma distribusi. Pemindahan titik kontrol pangan dari lumbung desa ke gudang korporasi bukanlah peristiwa netral. Ia adalah manifestasi dari kontradiksi inheren dalam kebijakan pangan negara. Negara, dalam logika kapitalisme agraria, terjebak dalam dilemma, yaitu menjaga legitimasi politik melalui harga pangan murah di kota, sekaligus melayani akumulasi modal agraria yang menuntut efisiensi, skala besar, dan terpusat.
Negara dalam Dua Wajah: Legitimasi dan Akumulasi
Dalam teori negara kapitalis yang dikembangkan oleh Nicos Poulantzas dan Bob Jessop, negara tidak berdiri di atas kepentingan rakyat secara utuh. Ia beroperasi dalam struktur kontradiktif, di satu sisi harus menjaga legitimasi politik, dengan menjaga harga beras tetap terjangkau, di sisi lain harus memastikan akumulasi kapital tetap berjalan. Seperti membuka ruang bagi korporasi pangan untuk menguasai distribusi pangan.
Kontradiksi ini tidak diselesaikan oleh negara. Sebaliknya, ia dipindahkan ke petani. Petani kecil, yang dulu menjadi aktor utama dalam sistem pangan lokal, kini hanya menjadi pemasok bahan mentah dalam rantai pasok yang dikendalikan oleh korporasi. Mereka kehilangan kontrol atas harga, distribusi, bahkan atas benih dan pupuk yang mereka gunakan.
Food Regime dan Dispossession: Teori Ekonomi-Politik Agraria
Dalam kerangka food regime yang dikembangkan oleh Philip McMichael, kita melihat bagaimana sistem pangan global bergerak dari rezim subsistensi ke rezim korporasi. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi ladang akumulasi kapital agraria melalui proses yang disebut accumulation by dispossession (David Harvey). Petani tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan kedaulatan atas pangan yang mereka hasilkan. Gudang korporasi menjadi simbol dari sistem ini, berorientasi efisien, terstandarisasi, tetapi jauh dari nilai-nilai lokal. Lumbung desa, yang dulu menjadi ruang kolektif dan simbol kemandirian, digantikan oleh sistem logistik yang tunduk pada algoritma pasar.
Karena kontradiksi ini tidak dapat diselesaikan secara internal karena kedua kekuatan tersebut saling menegasikan, negara memindahkan beban kontradiksi ke petani melalui proses akumulasi primitif. Proses ini berlangsung secara bertahap, melalui kebijakan yang tampak teknis tetapi berdampak structural, yaitu :
- Standarisasi Gudang, kebijakan ini mengubah logistik penyimpanan pangan dari sistem lokal, suatu sistem yang dahulu dikuasai petani dan menjadi sistem terpusat yang menguntungkan pelaku kapital.
- Hilangnya lumbung desa, hilangnya lembaga sosial dan ekonomi tradisional yang menjadi penyangga ketahanan pangan petani, menggantinya dengan ketergantungan pada pasar.
- Dispossession atas kedaulatan pangan, petani kehilangan kontrol atas benih, lahan, dan mekanisme produksi pangan, sehingga kedaulatan pangan mereka lenyap.
Dengan kata lain, negara tidak menyelesaikan kontradiksi, tetapi mengalihkan tekanan dari konflik politik ekonomi di kota ke tubuh petani, melalui proses dekomposisi agrarian sehingga hegemoni politik tetap terjaga di perkotaan, sementara desa menjadi wilayah ekstraksi untuk akumulasi kapital. Dengan kerangka ini, fenomena bukan sekadar “kebijakan teknis” logistik, melainkan re-artikulasi relasi kekuasaan dalam rantai pangan yang memperkuat posisi kapital agraria sembari melemahkan posisi petani.
Bila kita tetap pada kerangka di atas, maka “standarisasi gudang”, “hilangnya lumbung desa”, atau “regulasi logistik” bukanlah sebatas urusan infrastruktur atau efisiensi pasar, melainkan re-artikulasi relasi kekuasaan di dalam rantai pangan. Setiap titik dalam rantai benih, lahan, mesin panen, cold-storage dan transportasi menjadi arena baru di mana dapat diketahui bahwa, pertama (a) kapital agraria memperkuat posisinya yang memberikan informasi tentang standar volume, kualitas, dan waktu penyimpanan yang ditentukan di pusat, contohnya Jakarta atau Singapura yang membuat hanya pelaku dengan modal besar yang mampu memenuhi syarat. Berikutnya, (b). Skema kredit, asuransi, yang tersambung ke gudang-gudang besar melindungi kapital dari fluktuasi harga, sementara petani kecil justru terpapar langsung ke risiko pasar. Kedua, petani kehilangan “titik kendali” dengan fakta-fakta bahwa (a). lumbung desa yang tadinya menjadi buffer stok dan alat tawar (menahan jual saat harga turun) lenyap, (b). Penggusuran berlanjut dari lahan fisik ke arena non-fisik, seperti data panen, data cadangan gudang, akses ke platform logistik digital Dimana kesemua itu dikendalikan oleh kapital agraria atau platform digital milik konglomerasi. Ketiga, negara menegosiasikan ulang “konsensus” politiknya di kota, dengan Langkah-langkah (a). memindahkan beban ke petani, negara menjaga harga pangan di kota tetap stabil (murah), sehingga legitimasi “ketersediaan pangan” tetap terjaga, (b). konflik potensial antar buruh-konsumen urban versus kapital agraria tidak pernah meletus di dalam kota. Letusan itu dialihkan ke desa, berbentuk konflik petani versus perusahaan logistik, atau petani versus aparat penegak standar.
Dengan demikian, rantai pangan bukan lagi “saluran distribusi netral”, melainkan medium kekuasaan yang memproduksi kembali relasi dominasi, kapital agraria mengendalikan waktu, ruang, dan harga. Petani direposisikan sebagai “aktor tanpa buffer” yang harus menyesuaikan diri terhadap logika pasar yang semakin terpusat.
Di masa lalu, rantai pangan dipahami sebagai saluran distribusi yang netral, sebuah mekanisme teknis yang menghubungkan produksi dengan konsumsi, desa dengan kota, ladang dengan pasar. Namun dalam kenyataan kontemporer, rantai pangan telah mengalami mutasi paradigmatik, ia bukan lagi sekadar jalur logistik, melainkan medium kekuasaan yang secara aktif memproduksi dan mereproduksi relasi dominasi. Kapital agraria, dengan kekuatan modal dan teknologi, tidak hanya menguasai hasil panen, tetapi juga mengendalikan waktu, ruang, dan harga.
Dimensi waktu, musim tanam dan panen yang dahulu ditentukan oleh siklus alam dan kearifan lokal, kini tunduk pada kalender korporasi. Petani dipaksa menyesuaikan ritme hidupnya dengan jadwal distribusi, kontrak, dan permintaan pasar global. Dimensi ruang, yang mengartikulasikan bahwa ruang produksi pangan yang dahulu bersifat lokal dan beragam, kini diseragamkan oleh logika monokultur dan ekspansi agribisnis. Desa-desa berubah menjadi titik-titik produksi yang terintegrasi dalam rantai nilai global, kehilangan otonomi spasialnya. Dimensi harga, diketahui pula tentang harga pangan bahwa tidak lagi ditentukan oleh kebutuhan rakyat atau biaya produksi petani, melainkan oleh spekulasi pasar dan algoritma perdagangan. Petani menjadi produsen tanpa kuasa tawar, sementara konsumen menjadi pembeli tanpa kendali atas kualitas dan asal pangan.
Dalam struktur ini, petani direposisikan sebagai “aktor tanpa buffer”, dimana para petani tidak memiliki perlindungan sosial, cadangan pangan, atau kelembagaan yang dapat menahan guncangan pasar. Petani kecil harus menyesuaikan diri dengan logika yang tidak mereka ciptakan, dan sering kali tidak mereka pahami.
Paradigma ini menempatkan petani bukan sebagai subjek pembangunan, tetapi sebagai objek produksi. Mereka bukan lagi penjaga tanah dan benih, melainkan operator dalam sistem yang dikendalikan dari luar.
Implikasi paradigmatik dari transformasi ini memberikan artikulasi bahwa rantai pangan harus dipahami sebagai arena politik, bukan sekadar teknis, mengenai kebijakan pangan disadari tidak boleh netral, karena bentuk netralitas dalam struktur timpang berarti keberpihakan pada yang kuat, konsepsi tentang kedaulatan pangan harus direbut kembali melalui reposisi petani sebagai subjek utama, bukan sekadar pelaku pasif. Dengan demikian, perubahan kebijakan harus dimulai dari perubahan paradigma yang membalikkan artikulasi dari efisiensi ke keadilan, dari pasar ke komunitas dan dari kapital ke kedaulatan.