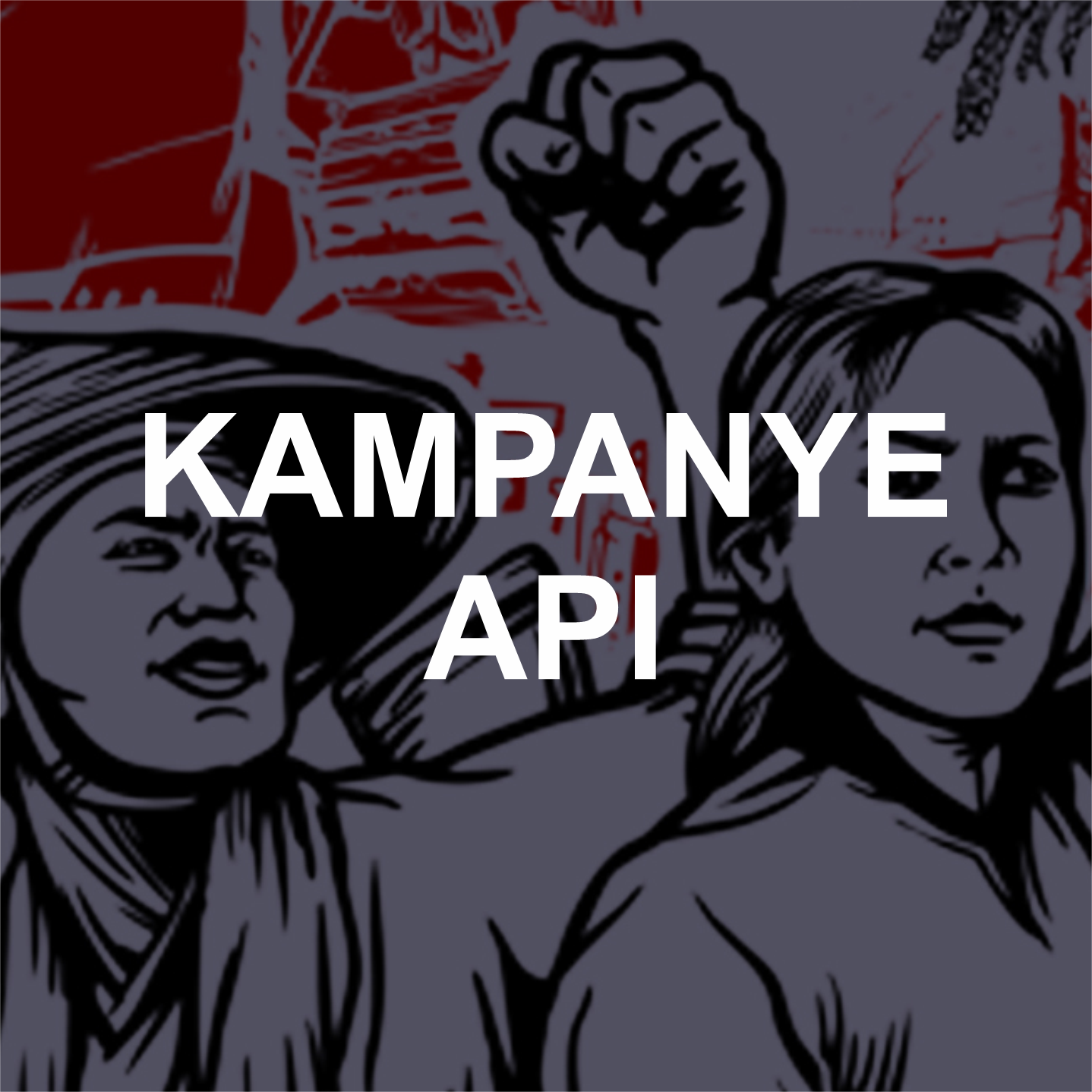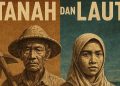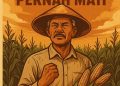Muhammad Nuruddin
Kalau esai sebelumnya kami mengisahkan entang ruang sidang, sebenarnya kami ingin mengajak pembaca untuk melihat sisi ruang lain yang tak kalah menegangkan dan mendebarkan, yakni ruang regulasi. Bedanya, di ruang sidang orang berdebat di depan hakim namun di ruang regulasi, orang berdebat di balik meja rapat, draft kebijakan, dan jargon teknokratis yang sering kali lebih rumit daripada soal matematika. Kami mempunyai nilai pemikiran secara positif induktif, bahwasanya aturan dibuat untuk melindungi segenap lapiran rakyat. Namun, makin kesini semakin sering kami membaca regulasi, semakin merasa aturan justru ditulis seperti resep rahasia restoran cepat saji. Sederhana di luar, tetapi penuh bahan tambahan yang hanya menguntungkan pemilik modal.
Sebagai contoh Undang-Undang tentang benih dan Perlindungan Varietas Tanaman, alih-alih membuka ruang bagi petani pada umumnya, regulasi itu sering kali dipenuhi lausul yang hanya bisa dipenuhi oleh korporasi, syarat laboratorium canggih, biaya pendaftaran selangit, hingga standar administratif yang mustahil dijangkau oleh petani kecil. Dalam banyak kasus, regulasi bekerja seperti pagar tak terlihat. Petani tidak langsung dilarang menanam atau menyilangkan benih, tapi ketika mereka melakukannya tanpa sertifikat resmi, tiba-tiba saja mereka bisa dituduh melanggar hukum. Korporasi punya jalur cepat dengan karpet merah, rakyat kecil harus antre di pintu belakang, kalau pintunya tidak digembok.
Revolusi Hijau Sebagai Revolusi Kebijakan
Perubahan kebijakan bukan tanpa sebab dan jejaknya dapat ditelusur sejak didisain tahun 80-an dan diadopsi oleh negara-negara berkembang dan mestinya ada latar belakang kuat yang mendasarinya. Jika kita mengenal Revolusi Hijau, maka kita akan memahami bagaimana politik pangan dikonstruksi. Revolusi Hijau tidak hanya soal teknologi, melainkan juga peralihan kebijakan, dari program diversifikasi ke program intensifikasi berbasis benih unggul. Sebelum tahun 1970-an, Diversifikasi tanaman pagan berupa ciri-cirinya tumpang-sari, tanaman lokal, minim input luar, kebijakan nasional, program “puso-sari” di pulau Jawa) dan sesudah tahun 1970-an, program Intensifikasi, satu komoditas utama (padi), benih unggul hibrida, pupuk-pestisida kimia, kredit input mensyaratkan paket “Panca Usaha Tani yang dikenal denan Green-Revolution. Diversifikasi, polyculture, tumpang-sari dinyatakan “tidak cukup meningkatkan produksi”, sehingga anggaran riset dan penyuluhan dialihkan ke Inmas atau Intensifikasi Massal yang hanya mensubsidi padi dan jagung unggulan.
Dampak langsung yang dihadapi masyarakat tani, benih lokal keluar dari subsidi resmi, petani harus menerima subsidi input berupa benih bersertifikat dan pupuk kimia setiap musimnya. Konsentrasi varietas padi menunjukkan >70 % sawah Indonesia ditanami <5 varietas padi hibrida pada 1980-an. Label “benih unggul” sekaligus menjadi alat standarisasi pasar, menyingkirkan benih lokal dan membuka pintu masuk perusahaan asing mulai dekade berikutnya. Revolusi Hijau sama dengan Revolusi Kebijakan dimana praktek yang berlaku selama ini terkait model dan praktek diversifikasi tanaman pangan di lahan pertanian di Indonesia mulai ditinggalkan dan diganti model input-intensif dorongan dari organisasi pangan dunia. Frame “tradisional sama artinya tidak efisien” diproduksi secara masif di media, kebijakan, dan riset pembangunan untuk melegitimasi alih fungsi subsidi ke benih paten bersertifikat dan unggul. Benih unggul bersertifikat menutup siklus ketergantungan, bahwa petani kecil dinyatakan “butuh modernisasi”, lalu dibelenggu hukum agar tidak bisa menabur ulang benihnya sendiri. Pencetus “Revolusi Hijau” oleh Direktur USAID William Gaud dan diumumkan pada tahun 1968 merujuk pada paket, benih unggul hibrida + pupuk sintetik + irigasi + pestisida.
Revolusi Hijau bermula dari perpaduan kekuatan politik yang dikendalikan oleh negara super power yang didukung oleh ilmuwan Norman Borlaug, dan korporasi transnasional kapital benih yang kemudian membentuk arsitektur pertanian industri global. Prestasi “menyelamatkan miliaran dari kelaparan” tidak bisa dipisahkan dari konsentrasi kekuasaan ekonomi politik atas benih, pupuk, dan pasar pangan dunia. Silahkan untuk dinilai sendiri oleh pembaca, apakah itu memang layak dianggap “perdamaian” atau sekadar “kemenangan pasar” berbaju ilmiah. Sebagaimana dinyatakan Henry Kissinger pada tahun 1970-an, “Jika Anda mengendalikan minyak, Anda mengendalikan negara, jika Anda mengendalikan pangan, Anda mengendalikan populasi.”
Fondasi Regulasi
Untuk memahami bagaimana kreativitas bisa begitu mudah dikapling, kita harus melihat fondasinya, regulasi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (HAKI). Sistem ini berdiri di atas beberapa undang-undang utama, yang masing-masing tampak netral di permukaan, tetapi bila ditelusuri, justru memberi ruang luas bagi korporasi untuk berkuasa. Ada Undang-Undang Paten, yang awalnya dirancang untuk melindungi penemu. Masalahnya, syarat pendaftaran paten menuntut biaya, birokrasi, dan standar yang mustahil dijangkau oleh petani atau perajin kecil. Akibatnya, yang bisa mendaftarkan paten hanyalah mereka yang punya modal besar, perusahaan transnasional dengan tim hukum lengkap. Lalu ada Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Dalam teksnya, PVT dimaksudkan untuk melindungi pemulia tanaman. Tapi dalam praktiknya, regulasi ini lebih sering menjadi alat monopoli. Petani kecil yang sudah turun-temurun menyilangkan benih dianggap tidak memenuhi standar administratif, sementara perusahaan bisa dengan mudah mendaftarkan varietas hasil “risetnya”, meski riset itu sering kali berangkat dari plasma nutfah lokal. Tak ketinggalan, Undang-Undang Hak Cipta dan Merek. Motif batik, lagu daerah, bahkan pengetahuan tradisional bisa diklaim pihak luar jika tidak didaftarkan lebih dulu. Artinya, beban perlindungan justru jatuh pada masyarakat lokal, padahal mereka tidak pernah membayangkan bahwa warisan leluhur harus dilindungi dengan dokumen hukum yang tebalnya setara skripsi.
Sistem ini ibarat pasar modern: penuh aturan, kamera pengawas, dan kasir digital. Rakyat kecil yang terbiasa dengan pasar tradisional tiba-tiba kebingungan. Mereka tidak ditolak secara langsung, tetapi dibuat tidak nyaman hingga akhirnya menyerah. Sementara itu, korporasi melenggang dengan mudah, karena memang pasar itu dibangun sesuai kebutuhan mereka. Lebih menyedihkan lagi, regulasi kita seringkali disusun dengan rujukan pada perjanjian internasional seperti TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Indonesia seakan-akan punya undang-undang sendiri, tapi hakikatnya banyak pasal yang sekadar “copy paste” dari aturan global. Dengan kata lain, regulasi lokal hanyalah cermin dari kepentingan global, bukan kebutuhan rakyat. Dalam kerangka seperti ini, jelas terlihat sistem HAKI di Indonesia bukan sekadar melindungi kreativitas, tapi menyeleksi siapa yang boleh disebut kreatif, dan siapa yang harus diam. Kami sering bertanya-tanya, bagaimana mungkin regulasi yang katanya dibuat “untuk kepentingan bangsa” justru terasa seperti kontrak eksklusif bagi segelintir perusahaan? Kadang kami berpikir, kalau saja kreativitas bisa dilobi di DPR, mungkin rakyat kecil juga akan dilindungi. Sayangnya, yang bisa melobi bukanlah mereka yang sibuk di sawah atau di laut, melainkan mereka yang sibuk di hotel bintang lima dan kota-kota metropolis dunia. Dan di situlah ironi itu menohok, regulasi bukan sekadar teks hukum, tapi pagar raksasa yang dipasang dengan rapi, agar siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus tetap di luar bisa ditentukan oleh segelintir orang.
Membaca regulasi HAKI sering membuat kami merasa seperti orang desa yang tersesat di mal mewah. Semuanya terang benderang, penuh etalase mengilap, tapi setiap kali saya mencoba menyentuh sesuatu, ada tulisan kecil bertuliskan “hanya untuk pelanggan VIP.” Sebagai pendamping petani dan komunitas, kami berkali-kali berhadapan dengan teks hukum yang seolah netral tapi diam-diam menyudutkan mereka. Kami ingat saat mencoba menjelaskan kepada seorang petani tentang syarat pendaftaran PVT. Ia mendengarkan serius, lalu menjawab, “Mas, kalau begitu saya harus jual berapa karung jagung buat bayar biaya daftar?” Kami berdua terdiam, lalu tertawa getir. Di situlah kami sadar: regulasi yang katanya melindungi, justru sudah memagari bahkan sebelum benih tumbuh. Regulasi yang lahir pasca Revolusi Hijau dan diperkuat oleh perjanjian global yang didukung kelompok terkaya diplanet ini secara bertahap memang membatasi hak petani kecil untuk mengembangkan, memperbanyak, mendistribusikan maupun “men-save” benihnya sendiri. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) serta “bayang-bayang paten” di sektor benih. Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjuta, kontrol negara atas pola tanam memberi pemerintah hak menetapkan wilayah, komoditas, dan teknik budidaya yang “diizinkan”. Petani yg mengumpulkan plasma nutfah atau membuat benih lokal wajib izin daerah; pelanggaran ancaman pidana. Putusan MK No. 99/2012 baru mencoret kewajiban izin bagi “petani kecil perorangan”, tapi tidak menghapus kewajiban izin untuk kegiatan kelompok/koperasi. TRIPs-WTO, merupakan fondemen global dimana Indonesia menandatangani TRIPs (1995) yang mempunyai kewajiban menyediakan perlindungan minimal 20 tahun untuk varietas atau proses benih. Tekanan ini muncul setelah fase intensifikasi Revolusi Hijau, begitu petani kecil sudah bergantung pada benih hibrida, pintu hukum ditutup agar mereka tidak bisa men-save dan jual kembali .
Efek Di Lapangan
Kasus kriminalisasi petani jagung (Jatim sepanjang tahun 2005-2020) dan kasus benih IF8 di kabupaten Aceh Utara (2019) karena “menabur ulang” benih komersial tanpa lisensi. Benih lokal hanya boleh beredar bila terdaftar dan dinamai pemerintah. Proses birokrasi tinggi membuat petani kecil urung mendaftarkan, lalu varietasnya di klaim sebagai “domain publik” dan dirakit industri menjadi varietas baru yang justru dilindung. Regulasi Perlindungan Varietas Tanaman, Paten, Sistem Budidaya Pertanian berkelanjutan dan kewajiban Trade Realted Intelectual Property Rights(TRIPs) yang ditransmisikan melalui program intensifikasi revolusi hijau memang mengkerdilkan hak petani kecil. Men-save benih unggul membutuhkan izin. Untuk memperbanyak dan menjual berpotensi pidana. Mengembangkan varietas sendiri , banyak prosedur, harus melewati uji baru dan biaya registrasi. Tukar-menukar informal dianggap legal hanya jika benih tidak tercantum dalam daftar varietas yang dilindungi. Dengan kata lain, “modernisasi” benih yang didanai revolusi hijau diikuti oleh kerangka hukum yang memindahkan kontrol benih dari tangan petani ke industri, sehingga petani kecil berubah dari pemulia sekaligus supplier menjadi konsumen tetap benih bermerek. Transformasi tanaman subsisten menjadi tanaman komoditas, program “Seed-Replacement-Rate” Indonesia menargetkan 90 % jagung lokal diganti hibrida sampai tahun 2030 dan subsidi langsung dialihkan jika petani memakai “seed certified” (hibrida). Bahkan ada laporan tentang varietas padi lokal yang diambil, didaftarkan ulang, lalu dijual kembali kepada petani dengan harga mahal. Bayangkan, benih yang berasal dari sawah mereka sendiri, kembali ke tangan mereka dalam bentuk kemasan plastik berlogo perusahaan.
Kasus-kasus ini menegaskan refleksi saya: regulasi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (HAKI) bukanlah ruang netral. Ia lebih mirip lapangan yang sejak awal sudah dimiringkan ke arah gawang korporasi. Petani, nelayan, pengrajin dan semua harus berlari menanjak, sementara perusahaan multinasional hanya perlu menendang bola sedikit untuk mencetak gol. Untuk benar-benar memahami mengapa regulasi HAKI di Indonesia sering terasa lebih ramah pada korporasi ketimbang pada rakyat, kita tidak bisa hanya berhenti di undang-undang nasional. Kita harus menengok ke “ruang rapat” yang lebih besar, organisasi perdagangan dunia, perjanjian internasional, dan meja negosiasi global yang seringkali lebih menentukan arah kebijakan kita daripada rapat di DPR.