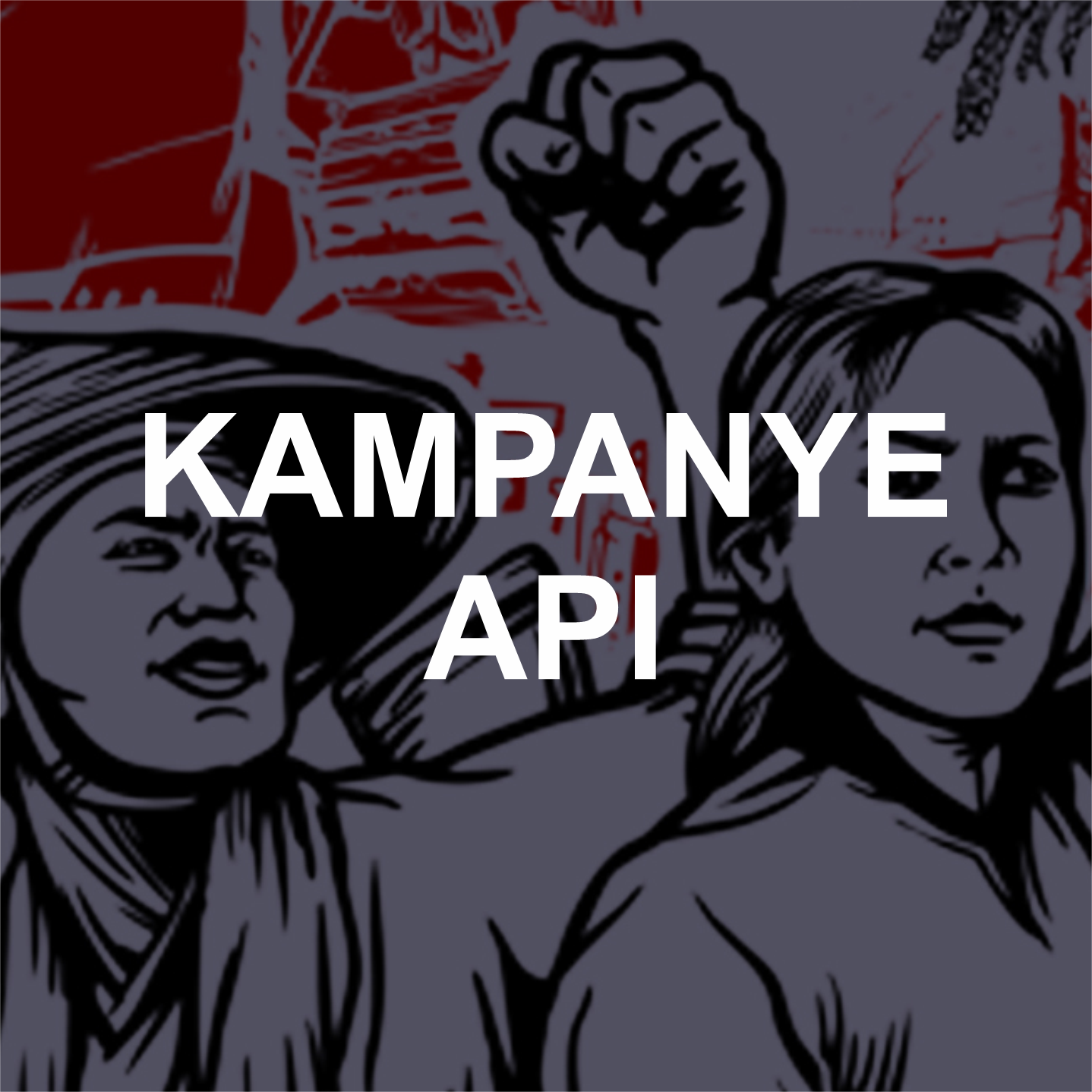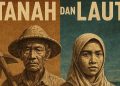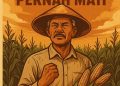Strategi Transformasi Sistem Pangan Desa di Indonesia
Muhammad Nuruddin
Latar Belakang Konteks
Sistem pangan beras di Indonesia merupakan struktur multidimensi yang terdiri dari empat subsistem utama: budidaya, perdagangan dan distribusi, konsumsi, serta cadangan pangan. Keempat subsistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan membentuk jaringan yang kompleks, di mana perubahan pada satu subsistem dapat memengaruhi stabilitas keseluruhan sistem pangan. Dalam konteks pembangunan pedesaan dan kedaulatan pangan, pemahaman terhadap keterkaitan antar subsistem menjadi krusial untuk merumuskan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.
Analisis mendalam yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional Aliansi Petani Indonesia (API) di berbagai wilayah anggota yang bergerak dalam produksi dan pengelolaan gabah serta beras, mengungkapkan adanya tantangan struktural yang signifikan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan akses terhadap sarana produksi, ketimpangan harga di tingkat petani, dominasi aktor pasar dalam distribusi, serta lemahnya kelembagaan cadangan pangan di tingkat komunitas. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pangan beras tidak hanya menghadapi persoalan teknis, tetapi juga persoalan kelembagaan, politik, dan sosial yang memerlukan pendekatan interdisipliner dan partisipatif. Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis tantangan dan peluang dalam sistem pangan beras di Indonesia, serta merumuskan strategi kebijakan berbasis komunitas yang dapat memperkuat kedaulatan pangan desa. Kajian ini berangkat dari pengalaman lapangan dan refleksi kolektif komunitas petani, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Penulisan artikel juga berfokus pada tantangan dan solusi dari perspektif Aliansi Petani Indonesia (API).
Kerangka Teoretis Sistem Pangan Beras
Sistem pangan beras dapat dianalisis secara akademik melalui tiga kerangka teoretis utama yang saling melengkapi. Masing-masing teori ini memberikan lensa unik untuk memahami dinamika, tantangan, dan kekuasaan dalam rantai pasok pangan.
Teori Sistem Sosial (Niklas Luhmann, 1995)
Dalam kerangka Teori Sistem Sosial Niklas Luhmann, transformasi sistem pangan petani bukanlah sekadar perubahan teknis atau ekonomi, melainkan sebuah proses internal yang berfokus pada perubahan komunikasi dan struktur operasional di dalam sistem itu sendiri. Sistem pangan petani dipandang sebagai sistem sosial yang otonom, yang memiliki logika dan cara beroperasinya sendiri.
Sistem Petani sebagai Sistem yang Beroperasi Secara Mandiri (Operatively Closed)
Sistem pangan petani, yang mencakup seluruh aktivitas dari budidaya hingga pasca panen, adalah sebuah sistem yang secara operasional tertutup (operativley closed). Ini berarti sistem tersebut tidak dapat dikendalikan langsung dari luar. Ia beroperasi berdasarkan komunikasi internalnya sendiri—misalnya, pengetahuan turun-temurun, ritual tanam, dan cara bertukar informasi antar petani.
- Transformasi tidak terjadi karena instruksi dari luar, tetapi karena sistem itu sendiri mengamati dan merespons gangguan atau iritasi dari lingkungannya (seperti kebijakan pemerintah, fluktuasi harga pasar, atau perubahan iklim).
- Sistem petani dapat memilih untuk menolak atau mengakomodasi gangguan tersebut, dan respons inilah yang memicu transformasi.
Hubungan dengan Lingkungan (Structural Coupling)
Hubungan antara sistem pangan petani dengan sistem-sistem sosial lainnya (seperti sistem pasar, sistem politik/kebijakan pemerintah, dan sistem ilmu pengetahuan) disebut kopling struktural (structural coupling). Melalui kopling ini, satu sistem dapat mengamati dan “mengganggu” sistem lainnya tanpa mengendalikannya. Dokumen laporan dari Aliansi Petani Indonesia mengidentifikasi “gangguan” dari luar, seperti dominasi pedagang/tengkulak dan kebijakan yang tidak mendukung. Ini adalah contoh bagaimana sistem pasar berinteraksi dengan sistem petani. Transformasi terjadi ketika sistem petani membentuk struktur baru—seperti “lembaga pangan komunitas” atau “manajemen RMU”—untuk mengubah cara mereka berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Struktur baru ini memungkinkan petani untuk memproses dan merespons iritasi dari pasar atau pemerintah dengan cara yang lebih menguntungkan bagi mereka, tidak lagi hanya menerima pasif.
Transformasi sebagai Proses Autopoiesis
Transformasi dalam pendekatan ini adalah proses autopoiesis—yakni, kemampuan sistem untuk mereproduksi dan mempertahankan dirinya sendiri melalui komponen-komponennya sendiri. Saat petani membentuk lumbung pangan atau manajemen RMU, mereka tidak hanya mengadopsi struktur baru, tetapi mereka juga menciptakan sistem komunikasi baru di mana mereka dapat bernegosiasi harga, mengelola pasokan, dan membuat keputusan kolektif.
- Ini adalah perubahan dari dalam, dari sebuah sistem yang reaktif terhadap gangguan eksternal (harga murah, saprodi mahal) menjadi sistem yang proaktif, yang mampu menciptakan logika operasionalnya sendiri untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan.
- Pada akhirnya, pendekatan sistem sosial menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi pangan petani tidak bergantung pada kebijakan top-down, melainkan pada kemampuan petani untuk membangun sistem sosial mereka sendiri yang kuat, mampu mengamati lingkungan dengan kritis, dan secara internal mereorganisasi diri mereka untuk mencapai tujuan mereka.
Teori Ketergantungan (Borras & Franco, 2012)
Teori Ketergantungan (Dependency Theory) menawarkan kerangka analisis yang kuat untuk memahami transformasi sistem pangan petani. Teori ini berfokus pada dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan yang mendasari hubungan antara petani (sebagai pihak periferi atau “pinggiran”) dan aktor-aktor yang lebih dominan seperti pedagang, tengkulak, dan pasar global (sebagai pihak pusat atau “inti”). Transformasi tidak dipandang sebagai proses linear kemajuan, melainkan sebagai upaya petani untuk membebaskan diri dari belenggu ketergantungan struktural.
Mekanisme Ketergantungan dan Eskploitasi
Dokumen awal dari API menggambarkan dengan jelas bagaimana mekanisme ketergantungan beroperasi dalam sistem pangan beras:
- Dominasi Pasar dan Harga: Petani terpaksa menjual gabah mereka dengan harga rendah kepada pedagang/tengkulak, sementara harga saprodi (benih, pupuk, pestisida) terus meningkat. Ini menciptakan kondisi di mana petani selalu “terjepit,” di mana keuntungan dari panen tidak cukup untuk menutupi biaya produksi, memaksa mereka terus meminjam dan semakin bergantung pada pedagang.
- Keterbatasan Akses Modal dan Infrastruktur: Kurangnya akses terhadap lembaga keuangan formal, gudang, dan penggilingan padi (RMU) menjadikan petani bergantung pada infrastruktur yang dikendalikan oleh pihak luar. Hal ini mencegah petani untuk mengelola hasil panen mereka sendiri dan memaksa mereka menerima harga yang ditawarkan oleh pedagang.
Strategi Transformasi untuk Melepaskan Diri dari Ketergantungan
Dari sudut pandang Teori Ketergantungan, transformasi pangan petani adalah proses melepaskan diri (disengaging) dari dominasi eksternal. Dokumen tersebut mengusulkan beberapa strategi yang sejalan dengan gagasan ini:
- Penguatan Kelembagaan Pangan Komunitas: Pembentukan dan penguatan organisasi petani adalah langkah krusial. Ini bukan hanya tentang berkumpul, tetapi tentang membangun kekuatan kolektif yang dapat menawar harga secara kolektif, mengakses modal, dan mengelola rantai pasok mereka sendiri. Lembaga ini berfungsi sebagai “mini-pusat” yang dikendalikan petani itu sendiri, mengurangi ketergantungan pada “pusat” eksternal.
- Pengendalian Infrastruktur dan Produksi: Inisiatif seperti mengelola RMU dan lumbung pangan di tingkat komunitas memungkinkan petani untuk mengontrol pasca panen dan penyimpanan, menghilangkan ketergantungan pada gudang pedagang. Demikian pula, praktik pembenihan komunitas adalah upaya untuk mengontrol input produksi, mengurangi ketergantungan pada perusahaan benih besar.
- Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan: Pelatihan teknik budidaya seperti SRI (System of Rice Intensification) dan peningkatan manajemen pasca panen memberdayakan petani dengan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Ini adalah bentuk kapasitas internal yang mengurangi kebutuhan untuk bergantung pada “ahli” eksternal.
Teori Ketergantungan melihat transformasi pangan petani sebagai perjuangan melawan ketidaksetaraan struktural. Keberhasilan transformasi diukur dari seberapa jauh petani dapat mengurangi ketergantungan mereka pada pasar dan aktor-aktor dominan, serta seberapa besar mereka mampu membangun kendali atas rantai nilai pangan mereka sendiri. Dari data yang terhimpun diperoleh informasi secara eksplisit menyoroti bagaimana petani terjepit oleh harga saprodi yang tinggi dan harga gabah yang rendah. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal dan gudang menjadikan petani bergantung pada pedagang dan tengkulak, yang memiliki kendali lebih besar dalam menentukan harga. Fenomena ini menciptakan ketergantungan struktural, di mana petani kesulitan untuk keluar dari siklus ekonomi yang tidak menguntungkan meskipun telah meningkatkan produktivitas.
Ekologi Politik Pangan (Patel, 2009; Altieri, 2009)
Ekologi Politik Pangan mengintegrasikan analisis lingkungan dengan analisis kekuasaan dan politik. Kerangka ini berargumen bahwa isu-isu lingkungan seperti degradasi lahan, kelangkaan air, dan serangan hama, bukanlah masalah murni alamiah, melainkan produk dari hubungan kekuasaan yang tidak setara. Akses terhadap sumber daya kunci seperti lahan, air, dan pupuk (saprodi) tidaklah sama bagi semua pihak. Akses ini sering kali dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, struktur pasar, dan kontrol oleh elit.
Politik Akses dan Penguasaan Sumber Daya
Teori ini berargumen bahwa isu-isu seperti konversi lahan dan kerentanan iklim bukanlah murni fenomena alam, melainkan hasil dari keputusan politik. Konversi lahan terjadi karena kebijakan yang memprioritaskan pembangunan properti atau industri di atas lahan pertanian produktif. Hal ini mencerminkan dominasi kepentingan kapitalis dan elit yang memiliki kekuasaan untuk mengubah tata ruang, menggeser petani dari lahan mereka. Dalam konteks air, ekologi politik menganalisis bagaimana sistem irigasi dan pengelolaan air dikontrol. Jika petani kecil tidak memiliki akses yang setara terhadap air, sementara korporasi atau perkebunan besar mendapat prioritas, maka kerentanan terhadap kekeringan bukan lagi masalah cuaca, melainkan ketidakadilan politik.
Kendali Atas Input dan Rantai Produksi
Ekologi politik pangan juga menyoroti bagaimana rantai pasok input pertanian seperti benih, pupuk, dan alsintan dikendalikan oleh segelintir perusahaan besar. Dominasi ini menciptakan ketergantungan struktural pada petani, yang dipaksa membeli input mahal dari korporasi yang memiliki monopoli atau oligopoli. Dengan kata lain, keuntungan dari praktik pertanian tidak sepenuhnya kembali ke petani, tetapi terdistribusi ke perusahaan-perusahaan yang mengendalikan input dan pasar. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun harga beras tinggi, petani tetap terjepit oleh biaya produksi yang membengkak.
Strategi Perlawanan dan Otonomi
Dalam kerangka ekologi politik, transformasi sistem pangan petani adalah sebuah perjuangan politik untuk mendapatkan kembali otonomi dan kendali. Strategi yang diusulkan oleh Aliansi Petani Indonesia (API) dapat dilihat sebagai tindakan politik yang menantang struktur kekuasaan yang ada.
Pembenihan Komunitas. Praktik ini adalah tindakan politik untuk menantang dominasi perusahaan benih, memastikan petani memiliki kontrol atas sumber daya genetik mereka sendiri.
Pengelolaan Lumbung Pangan dan RMU: Ini adalah upaya untuk menciptakan infrastruktur tandingan yang berada di luar kendali pasar dominan, memungkinkan petani untuk mengendalikan distribusi dan harga produk mereka.
Pada akhirnya, pendekatan ekologi politik menunjukkan bahwa kedaulatan pangan bukan hanya tentang kemampuan memproduksi makanan yang cukup, tetapi tentang hak untuk menentukan sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan otonom, yang didasarkan pada kendali petani atas sumber daya dan keputusan politik.
Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif dalam Analisis Sistem Pangan Petani
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus dan analisis dokumen, sebuah metode yang relevan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks. Metodologi ini sejalan dengan pandangan fenomenologi (Edmund Husserl), yang berupaya memahami pengalaman hidup subjek dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam konteks ini, peneliti berupaya memahami realitas sistem pangan dari perspektif petani, bukan dari data kuantitatif yang kering.
Pengumpulan Data dan Sumber Informasi
Pengumpulan data primer dilakukan melalui diskusi komunitas partisipatif yang difasilitasi oleh Sekretariat Nasional Aliansi Petani Indonesia (API). Pendekatan ini selaras dengan metode penelitian partisipatoris (Participatory Action Research – PAR) yang dikembangkan oleh Paulo Freire. PAR menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya dihasilkan oleh peneliti, tetapi juga oleh partisipan melalui proses dialog dan refleksi kolektif. Dengan melibatkan petani, perempuan, pemuda, dan perangkat desa, penelitian ini memastikan bahwa suara-suara dari akar rumput didengar dan diakui. Data sekunder, yang menjadi pelengkap data primer, dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk:
- Dokumen kebijakan pemerintah terkait pangan.
- Laporan Musyawarah Desa (Musdes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
- Publikasi internal API yang mendokumentasikan praktik-praktik baik sistem pangan komunitas.
Penggunaan beragam sumber data ini merupakan bentuk triangulasi data, sebuah konsep yang ditekankan oleh Norman K. Denzin. Triangulasi bertujuan untuk memvalidasi temuan dengan membandingkan informasi dari sumber yang berbeda, sehingga meningkatkan kredibilitas dan keandalan penelitian.
Analisis Data dan Teori
Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana peneliti mengidentifikasi dan mengelompokkan pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data. Tema-tema ini kemudian dikaitkan dengan empat subsistem utama yang telah didefinisikan dalam dokumen: budidaya, distribusi, konsumsi, dan cadangan pangan. Untuk memperkuat validitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi metode melalui:
- Observasi lapangan: Peneliti secara langsung mengamati praktik kelembagaan pangan di desa, memvalidasi temuan diskusi dengan realitas di lapangan.
- Wawancara semi-terstruktur: Wawancara mendalam dengan fasilitator komunitas memberikan perspektif tambahan dan memungkinkan peneliti untuk menggali detail yang mungkin tidak muncul dalam diskusi kelompok.
- Analisis visual: Analisis terhadap peta rantai pangan dan kartu indikator yang dibuat oleh komunitas membantu peneliti memahami secara visual bagaimana petani melihat dan mengorganisir sistem pangan mereka.
Penggunaan metode yang berlapis ini memastikan bahwa temuan yang dihasilkan tidak bias dan merepresentasikan realitas yang kompleks dari sistem pangan petani. Dengan mengintegrasikan data dari diskusi, dokumen, observasi, dan wawancara, penelitian ini membangun argumen yang solid dan terjustifikasi.
Hasil dan Implementasi
Hasil dari analisis ini tidak hanya digunakan untuk menyusun laporan ilmiah, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan desain alat bantu visual. Proses ini selaras dengan prinsip penelitian aksi (action research), yang menekankan bahwa tujuan penelitian bukan hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk menciptakan perubahan positif. Alat bantu visual ini, yang dapat digunakan dalam pelatihan, advokasi, dan perencanaan desa, menjadi jembatan antara temuan akademis dengan praktik nyata di lapangan, memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dapat memberdayakan komunitas secara berkelanjutan.
Hasil dan Pembahasan
Tantangan Struktural dalam Sistem Pangan Beras
Analisis yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional Aliansi Petani Indonesia (API) di berbagai wilayah anggota menunjukkan bahwa sistem pangan beras di tingkat desa menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan saling terkait antar subsistem. Empat subsistem utama, budidaya, distribusi, konsumsi, dan cadangan pangan menunjukkan :
- Budidaya, konversi lahan pertanian, masalah ketersediaan air (banjir dan kekeringan), serangan hama penyakit tanaman (HPT), dan ketersediaan sarana produksi pertanian (saprodi) yang terbatas dan mahal, seringkali berujung pada gagal panen. Ketergantungan terhadap input eksternal dan minimnya pelatihan budidaya lestari menyebabkan rendahnya produktivitas dan keberlanjutan.
- Distribusi dan Perdagangan, harga gabah di tingkat petani cenderung rendah, menyebabkan petani “terjepit” saat harus membeli saprodi untuk musim tanam berikutnya. Petani tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan nilai jual gabah, sementara biaya produksi terus meningkat. Kurangnya manajemen pasca panen yang memadai di tingkat komunitas juga menyebabkan tingginya kehilangan hasil.
- Konsumsi: Masyarakat desa, termasuk petani, sering kali tidak mengonsumsi beras hasil produksi lokal karena sistem distribusi yang tidak efisien dan preferensi pasar terhadap varietas tertentu. Hal ini menunjukkan adanya keterputusan antara produksi dan konsumsi lokal.
- Cadangan Pangan, Sebagian besar desa tidak memiliki sistem cadangan pangan yang terorganisir. Ketika terjadi gagal panen atau lonjakan harga, komunitas menjadi sangat rentan dan bergantung pada bantuan eksternal.
Strategi Komunitas dan Inovasi Lokal
Meskipun menghadapi tantangan, beberapa komunitas menunjukkan kapasitas inovatif dalam membangun sistem pangan yang lebih mandiri dan berkeadilan untuk membangun kedaulatan pangan yang berpusat pada penguatan komunitas. Strategi yang ditemukan antara lain:
Forum Pangan Desa: Dibentuk sebagai ruang deliberatif untuk memperkuat organisasi petani, Bumdesa dan lembaga pangan komunitas serta menentukan harga lokal, mengatur distribusi, dan merancang kebijakan pangan desa.. Ini termasuk manajemen RMU dan lumbung pangan di tingkat desa atau komunitas, yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan distribusi mandiri.Peningkatan Kapasitas Budidaya dan Pasca Panen: Inisiatif seperti pelatihan teknik budidaya lestari, seperti budidaya sistem jajae legowo, System of Rice Intensification (SRI), dan praktik pembenihan komunitas mengurangi ketergantungan terhadap benih komersial dan memperkuat adaptasi terhadap kondisi agroekologi setempat dianjurkan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian petani. Peningkatan kapasitas manajemen pasca panen, khususnya di tingkat RMU, juga menjadi prioritas.
Lumbung Pangan Komunitas: Beberapa desa mengaktifkan kembali lumbung pangan sebagai cadangan strategis. Lumbung ini dikelola secara kolektif dan digunakan untuk kebutuhan darurat atau stabilisasi harga.
Pelibatan Perempuan dan Pemuda: Kelembagaan pangan yang melibatkan perempuan dan pemuda menunjukkan tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi. Mereka berperan dalam inovasi teknologi, pengelolaan kelembagaan, dan kampanye konsumsi pangan lokal.
Keberhasilan transformasi diukur dari seberapa jauh petani dapat mengurangi ketergantungan mereka pada pasar dan aktor-aktor dominan, serta seberapa besar mereka mampu membangun kendali atas rantai nilai pangan mereka sendiri.
Keberhasilan transformasi sistem pangan petani, dari perspektif akademik, bukanlah sekadar peningkatan pendapatan atau hasil panen. Hal ini adalah proses kompleks yang melibatkan restrukturisasi hubungan kekuasaan, otonomi sistem internal, dan kendali atas sumber daya. Pengukurannya dapat diuraikan melalui perpaduan teori-teori sosiologi dan ekologi politik
Pengukuran Keberhasilan Melalui Teori Ketergantungan
Dari sudut pandang Teori Ketergantungan (Dependency Theory), keberhasilan diukur dari seberapa jauh petani dapat melepaskan diri (disengaging) dari struktur eksploitatif yang dikendalikan oleh “pusat” (pedagang, tengkulak, pasar global). Transformasi dianggap berhasil ketika :
- Pembentukan ‘Mini-Pusat’, Petani berhasil membangun kelembagaan kolektif, seperti lumbung pangan atau koperasi, yang berfungsi sebagai “mini-pusat” ekonomi mereka sendiri. Ini memungkinkan mereka untuk menawar harga, mengelola pasokan, dan mengakses modal secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada aktor dominan eksternal.
- Pengendalian Rantai Nilai: Keberhasilan tercermin dari kemampuan petani untuk mengendalikan tahapan kritis dalam rantai nilai pangan, mulai dari produksi benih, pengelolaan panen, hingga pemasaran. Contohnya, praktik pembenihan komunitas secara langsung mengurangi ketergantungan pada perusahaan benih besar, sementara pengelolaan RMU (Rice Milling Unit) secara kolektif memberikan kontrol atas kualitas dan harga beras.
Pengukuran Keberhasilan Melalui Teori Sistem Sosial (Niklas Luhmann)
Dalam kerangka Teori Sistem Sosial, keberhasilan transformasi diukur dari kemampuan sistem pangan petani untuk mencapai otonomi dan menjadi autopoietik (mampu mereproduksi dirinya sendiri).
- Pergeseran dari Reaktif ke Autopoietik: Sistem yang berhasil adalah sistem yang tidak lagi hanya bereaksi terhadap “iritasi” dari lingkungannya (seperti harga yang ditetapkan pasar atau kebijakan pemerintah), melainkan sistem yang secara internal dapat mengelola iritasi tersebut dan meresponsnya dengan cara yang menguntungkan. Keberhasilan ini ditandai oleh terbentuknya komunikasi baru di antara petani, seperti musyawarah untuk menentukan harga bersama atau mekanisme internal untuk mengelola cadangan pangan.
- Pembentukan Struktur Internal Baru: Keberhasilan ini terwujud dalam struktur sosial yang dibentuk oleh petani sendiri (seperti forum petani atau tim manajemen lumbung), yang berfungsi sebagai “organ” sistem yang memproses informasi dan membuat keputusan secara kolektif, bukan atas dasar instruksi dari luar.
Pengukuran Keberhasilan Melalui Perspektif Ekologi Politik
Ekologi Politik melihat keberhasilan bukan hanya dari aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga dari aspek kendali atas ekologi produksi.
- Akses dan Kendali Sumber Daya: Keberhasilan diukur dari seberapa besar petani dapat mendapatkan kembali kontrol atas sumber daya alam yang penting seperti lahan dan air, yang sering kali dipengaruhi oleh kebijakan politik. Praktik budidaya lestari seperti SRI (System of Rice Intensification) tidak hanya meningkatkan hasil, tetapi juga merupakan pernyataan politik bahwa petani dapat mengelola lahan dan air mereka secara berkelanjutan tanpa bergantung pada input kimia yang mahal.
- Kedaulatan Pangan Sejati: Puncaknya, keberhasilan diukur dari pencapaian kedaulatan pangan—sebuah konsep yang melampaui ketahanan pangan. Kedaulatan pangan berarti bahwa masyarakat memiliki hak untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri, yang mencakup kontrol penuh atas sumber daya produksi, pasar, dan kebijakan.
Rekomendasi Kebijakan
Artikel ini merumuskan tujuh pilar kebijakan:
Desentralisasi tata kelola pangan ke tingkat desa.
Kebijakan pangan selama ini cenderung bersifat top-down dan seragam, tidak memperhatikan keragaman ekologi, budaya, dan kebutuhan lokal. Desentralisasi memungkinkan desa memiliki kewenangan untuk merancang sistem pangan sesuai konteksnya, termasuk pengelolaan benih, distribusi hasil panen, dan cadangan pangan. Ini sejalan dengan semangat UU Desa dan prinsip kedaulatan pangan.
Revitalisasi kelembagaan pangan lokal melalui Dana Desa.
Lembaga seperti lumbung pangan, koperasi tani, dan forum pangan desa adalah instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Namun, banyak yang tidak aktif atau belum difungsikan secara optimal. Revitalisasi mencakup penguatan kapasitas, dukungan anggaran melalui Dana Desa, dan integrasi kelembagaan ini ke dalam RPJMDes dan Musyawarah Desa.
Reformasi harga dan distribusi berbasis keadilan.
Petani sering kali tidak menikmati harga yang adil karena dominasi tengkulak dan spekulan. Reformasi harga mencakup peninjauan ulang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) agar mencerminkan biaya produksi dan margin wajar. Distribusi berbasis komunitas—misalnya melalui koperasi atau pasar desa—dapat memutus rantai distribusi yang eksploitatif dan meningkatkan posisi tawar petani.
Kemandirian teknologi dan benih lokal.
Ketergantungan pada benih dan teknologi dari luar membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga dan regulasi. Kemandirian dicapai melalui penangkaran benih lokal, pelatihan budidaya lestari (misalnya tanam padi sistem jajar legogowo, SRI – System of Rice Intensification), dan penguatan hak petani atas sumber daya genetik. Ini juga mendukung keberlanjutan ekologi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Cadangan pangan komunitas minimal 3 bulan konsumsi.
Cadangan pangan desa berfungsi sebagai penyangga saat terjadi krisis (gagal panen, bencana, lonjakan harga). Lumbung pangan yang dikelola komunitas dapat menjamin ketersediaan pangan minimal untuk 3 bulan konsumsi. Kebijakan ini memperkuat ketahanan lokal dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.
Peran perempuan dan pemuda dalam sistem pangan.
Perempuan dan pemuda sering kali menjadi aktor kunci dalam produksi dan inovasi pangan, namun kurang diakui dalam pengambilan keputusan. Kebijakan inklusif harus memastikan keterlibatan mereka dalam kelembagaan pangan, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya. Ini juga penting untuk regenerasi petani dan keberlanjutan sistem pangan desa.
Monitoring dan evaluasi partisipatif berbasis indikator lokal.
Evaluasi kebijakan pangan harus melibatkan komunitas secara aktif, bukan sekadar laporan teknokratik. Indikator kedaulatan pangan berbasis lokal—misalnya akses benih, peran perempuan, cadangan pangan—dapat digunakan dalam Musyawarah Desa dan RPJMDes. Ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pembelajaran kolektif.
Kesimpulan
Sistem pangan beras di Indonesia, yang terdiri dari subsistem budidaya, distribusi, konsumsi, dan cadangan pangan, menunjukkan kerentanan struktural yang saling terkait. Temuan lapangan dari wilayah kerja Aliansi Petani Indonesia (API) mengungkapkan bahwa ketimpangan akses terhadap input produksi, dominasi pasar dalam distribusi, keterputusan antara produksi dan konsumsi lokal, serta lemahnya kelembagaan cadangan pangan telah menghambat terciptanya sistem pangan yang adil dan berkelanjutan. Namun demikian, berbagai inovasi komunitas menunjukkan bahwa desa memiliki kapasitas untuk membangun sistem pangan alternatif yang berbasis nilai lokal, solidaritas, dan kemandirian. Forum pangan desa, penangkaran benih lokal, lumbung pangan komunitas, serta pelibatan perempuan dan pemuda merupakan contoh praktik transformatif yang dapat direplikasi dan diperkuat melalui kebijakan publik.
Dengan mengadopsi pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, kebijakan pangan nasional dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, memperkuat kedaulatan pangan desa, dan mendorong transformasi sistem pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Daftar Pustaka
- Altieri, M. A. (2009). Agroecology, small farms, and food sovereignty. Monthly Review, 61(3), 102–113.
- Borras, S. M., & Franco, J. C. (2012). Global land grabbing and trajectories of agrarian change. Journal of Agrarian Change, 12(1), 34–59.
- Luhmann, N. (1995). Social Systems. Stanford University Press.
- Patel, R. (2009). Food sovereignty. The Journal of Peasant Studies, 36(3), 663–706.
- Aliansi Petani Indonesia. (2016). Mata Rantai Pangan Beras: Diskusi dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta: API.